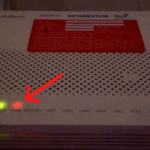Di tengah situasi yang penuh tantangan, banyak individu mempertimbangkan untuk meninggalkan Indonesia dan menetap di negeri orang. Keputusan seperti ini bukanlah hal baru dan telah dilakukan oleh berbagai kalangan, termasuk tokoh ekonomi sekaligus pejabat negara, Sumitro Djojohadikusumo, beserta keluarganya.
Sumitro merupakan sosok penting dalam sejarah ekonomi Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada periode 1950-1951, serta Menteri Keuangan pada 1952-1953. Sebagai seorang ekonom berpengaruh, ia memiliki kedekatan dengan Presiden Soekarno dan turut andil dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional.
Namun, seiring berjalannya waktu, arah perjuangannya bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Sumitro memutuskan bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera, sebuah gerakan yang lahir sebagai bentuk protes terhadap sistem pemerintahan yang terlalu terpusat dan kurang memberikan perhatian terhadap daerah.
Sejarawan Audrey Kahin dalam bukunya Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998 (2005) mengungkapkan bahwa saat PRRI mendeklarasikan diri pada 15 Februari 1958, Sumitro, yang sebelumnya merupakan kader Partai Sosialis Indonesia (PSI), diangkat sebagai Menteri Perdagangan dan Perhubungan dalam pemerintahan tandingan tersebut.
Tidak lama setelah deklarasi tersebut, pemerintah pusat bereaksi keras. Gerakan PRRI dianggap sebagai ancaman serius terhadap stabilitas negara, sehingga tindakan represif dilakukan terhadap para tokoh yang terlibat, termasuk Sumitro. Mereka yang berperan aktif dalam gerakan ini menghadapi risiko penangkapan.
“Di mata mereka, itu mengkhianati tujuan kemerdekaan yang dituju oleh pusat dan daerah sejak tahun-tahun awal abad ini,” ujar Audrey Kahin.
Meski demikian, Sumitro meyakini bahwa keterlibatannya dalam PRRI merupakan bentuk perjuangan menuntut keadilan bagi daerah-daerah yang merasa kurang diperhatikan. Sejak Indonesia merdeka, alokasi anggaran untuk daerah dinilai tidak sebanding dengan dana yang mengalir ke pusat.
“Dalam hati Sumitro mengeluh ‘mereka berkuasa dan hendak menguasai daerah melalui anggaran’,” demikian tertulis dalam biografi resminya, Jejak Perlawanan Begawan Pejuang (2001).
Hidup di Pengasingan Bersama Keluarga
Selama aktif dalam PRRI, Sumitro tidak sendirian. Ia telah berkeluarga dengan Dora Sigar dan memiliki empat anak: Bianti, Maryani, Prabowo, dan Hashim. Namun, situasi politik yang semakin memanas membuatnya harus meninggalkan Indonesia. Pada pertengahan 1957, ia memutuskan untuk membawa serta istri dan anak-anaknya ke luar negeri guna mencari dukungan internasional.
Namun, langkah tersebut tidak berjalan sesuai harapan. PRRI akhirnya gagal, dan pemerintah pusat berhasil meredam gerakan tersebut. Sumitro pun tidak bisa kembali ke Indonesia, karena jika nekat pulang, ia berisiko ditangkap oleh pemerintahan Soekarno. Akibatnya, ia dan keluarganya menjalani hidup di perantauan dalam waktu yang cukup lama.
Mereka berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, termasuk Singapura, Hong Kong, Kuala Lumpur, Zurich, London, dan Bangkok. Saat meninggalkan Indonesia, anak-anaknya masih sangat kecil. Prabowo, misalnya, baru berusia lima tahun, sementara Hashim, anak bungsunya, masih berusia tiga tahun.
Dalam Jejak Perlawanan Begawan Pejuang (2001), Sumitro mengenang bahwa anak-anaknya memiliki semangat juang yang tinggi. Salah satu yang paling vokal adalah Prabowo, yang sering kali merasa tidak nyaman tinggal di luar negeri karena ejekan yang diterimanya sebagai orang Indonesia.
“Kenapa bawa kita ke negeri ini? Saya tahu Papi berseberangan dengan Soekarno. Tapi, saya tidak tahan, semua meledek negara kita. Kalau sampai satu tahun lagi saya di sini, saya akan menjadi pro Soekarno,” protes Prabowo kepada ayahnya.
Bertahan Hidup dan Menyesuaikan Diri
Di perantauan, Sumitro berusaha mencari nafkah dengan berbisnis di bidang mebel dan properti. Meski jauh dari tanah air, ia tetap memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik. Keuletannya pun membuahkan hasil, terbukti dengan prestasi akademik anak-anaknya yang membanggakan.
Jurnalis Thress Nio dalam tulisannya di Kompas (11 Juli 1967) berjudul “Kisah Pengembaraan Keluarga Dr. Sumitro” menuturkan bahwa anak pertama Sumitro, Bianti, berhasil masuk Universitas Wisconsin. Sementara itu, Prabowo menunjukkan kecerdasan luar biasa dengan naik kelas lebih cepat dibanding teman-temannya.
Namun, ada konsekuensi dari hidup di luar negeri. Anak-anak Sumitro tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, bahkan Hashim sama sekali tidak menguasainya.
“Hashim ketika meninggalkan Indonesia baru berusia 3 tahun, kini sama sekali tidak dapat berbahasa Indonesia,” tulis Thress Nio.
Meski demikian, Prabowo tetap menjadi pusat perhatian di lingkungan barunya. Ketika tinggal di London, ia yang berusia 15 tahun kerap mendapat telepon dari gadis-gadis sebaya yang tertarik padanya. Dengan wajah khas Asia yang eksotis, ia menjadi daya tarik bagi remaja Inggris saat itu.
Akhir Pengembaraan dan Kembali ke Indonesia
Pelarian panjang keluarga Sumitro akhirnya menemui titik akhir ketika terjadi perubahan kepemimpinan di Indonesia. Setelah Soeharto resmi menjadi Presiden pada 1967, Sumitro merasa aman untuk kembali ke tanah air. Keputusan ini membawa keluarganya kembali ke kehidupan baru di Indonesia.
Kepulangan Sumitro pun membuka lembaran baru bagi keluarganya. Ia kembali berkiprah di pemerintahan dengan menjabat sebagai Menteri Riset pada era Soeharto. Sementara itu, Prabowo menempuh jalur militernya dengan masuk Akademi Militer pada tahun 1973.
Kisah keluarga Sumitro Djojohadikusumo menjadi salah satu contoh bagaimana perjalanan hidup bisa berliku akibat dinamika politik. Dari seorang pejabat tinggi negara, kemudian menjadi pengasingan politik, hingga akhirnya kembali membangun karier di Indonesia, perjalanan mereka mencerminkan ketahanan dan adaptasi dalam menghadapi perubahan zaman.