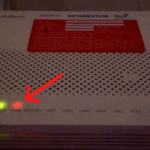Kondisi panas antara India dan Pakistan belakangan ini memang tidak disertai dengan ancaman langsung berupa pernyataan perang terbuka. Namun, tindakan-tindakan saling membalas secara militer, komunikasi yang mengandung pesan tersembunyi, serta intervensi diplomatik global yang semakin gencar, telah menumbuhkan kekhawatiran lama yang sempat mereda: potensi meletusnya konflik nuklir di Asia Selatan.
Meskipun eskalasi ini belum mengarah pada benturan nuklir secara nyata, rangkaian insiden terkini menjadi alarm keras bahwa konflik dua negara bertetangga ini bisa sewaktu-waktu menjelma menjadi mimpi buruk global. Situasi di kawasan tersebut, seperti api kecil yang ditiup angin kencang, berisiko menjalar menjadi kobaran besar yang sulit dikendalikan.
Beberapa ilmuwan telah memetakan bagaimana skenario terburuk bisa terjadi. Salah satunya, riset pada 2019 yang dilakukan oleh tim internasional, memulai model prediktifnya dengan gambaran kelam: sebuah serangan teroris terhadap parlemen India pada tahun 2025 yang kemudian memantik pertikaian nuklir dengan Pakistan.
Enam tahun setelah riset tersebut, realitas geopolitik menunjukkan babak baru. Ketegangan yang meruncing—meskipun sempat ditenangkan oleh kesepakatan gencatan senjata berkat peran Amerika Serikat pada Sabtu (10/05)—telah menyulut ingatan kolektif tentang rapuhnya perdamaian di kawasan.
Sementara suhu krisis meningkat, Pakistan menunjukkan sikap dua wajah: merespons lewat aksi militer sekaligus mengumumkan pertemuan Otoritas Komando Nasional (NCA), sebuah isyarat kuat kepada dunia tentang senjata pemusnah massal yang mereka miliki. NCA, sebagai lembaga strategis, memiliki otoritas penuh atas kendali serta potensi peluncuran senjata nuklir Pakistan.
Motif di balik langkah tersebut belum dapat dipastikan sepenuhnya—apakah murni untuk pertunjukan simbolik, strategi tekanan psikologis, atau memang sinyal bahaya yang sebenarnya. Momen ini pun beriringan dengan munculnya kabar bahwa Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, turut turun tangan menenangkan ketegangan.
Presiden AS Donald Trump bukan hanya memediasi gencatan senjata, tetapi juga bertindak sebagai penghalang potensial pecahnya “perang nuklir”.
Dalam pidatonya pada Senin (12/05), Perdana Menteri India Narendra Modi menegaskan: “India tak akan terintimidasi oleh ancaman nuklir.”
“Tiap tempat berlindung teroris yang beroperasi dengan dalih ini menghadapi serangan yang tepat dan tegas,” tambah Modi.
Menurut data dari Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), kedua negara memiliki kekuatan nuklir yang cukup untuk memusnahkan kota dalam sekejap—masing-masing sekitar 170 hulu ledak nuklir. Secara global, hingga Januari 2024, jumlah total hulu ledak diperkirakan mencapai 12.121 unit, di mana 9.585 disimpan di pangkalan militer, dan sekitar 3.904 dalam status siaga.
Dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan Rusia, menguasai sekitar 8.000 senjata tersebut.
Menurut Christopher Clary, pakar keamanan dari Universitas Albany di AS, mayoritas hulu ledak India dan Pakistan didesain untuk diluncurkan dari daratan. Namun, kedua negara kini sedang membangun sistem peluncuran tiga matra—darat, udara, dan laut—untuk meningkatkan daya jangkau dan opsi serangan.
“Kemungkinan besar India memiliki kekuatan udara (pesawat yang mampu membawa senjata nuklir) yang lebih besar daripada Pakistan,” ujar Clary kepada BBC.
“Meskipun kita paling sedikit tahu tentang kekuatan laut Pakistan, masuk akal untuk menilai kekuatan laut India lebih maju dan lebih mumpuni dibandingkan dengan kekuatan nuklir berbasis laut Pakistan,” lanjutnya.
Salah satu penyebab ketimpangan itu, jelas Clary, adalah minimnya alokasi dana dan waktu dari Pakistan dalam membangun armada kapal selam nuklir, sehingga memberikan India keunggulan yang jelas dari segi kualitas kekuatan laut.
Sejak melakukan uji coba nuklir pada 1998, Pakistan tidak pernah secara resmi mengumumkan doktrin nuklir mereka. Sebaliknya, India menyatakan kebijakan “no-first use”—tidak akan menggunakan senjata nuklir kecuali jika terlebih dahulu diserang dengan senjata serupa.
Namun, sikap India tersebut mulai menunjukkan kelenturan. Pada 2003, negara itu membuka kemungkinan menggunakan senjata nuklir sebagai respons terhadap serangan kimia atau biologis, yang berarti doktrinnya tak lagi sesederhana dulu. Pada 2016, pernyataan Menteri Pertahanan saat itu, Manohar Parrikar, yang menyebut India sebaiknya tidak “terkekang” oleh kebijakan tersebut, memicu keraguan baru—meski ia kemudian mengklarifikasi bahwa itu hanya pandangan pribadi.
Menurut Sadia Tasleem dari Carnegie Endowment for International Peace, sekalipun Pakistan tak punya doktrin tertulis, pernyataan resmi dan pola perkembangan senjata memberikan gambaran tentang orientasi militernya.
Sejumlah kondisi yang bisa memicu serangan nuklir Pakistan telah dijelaskan oleh Khalid Kidwai pada 2001: kehilangan wilayah vital, kerusakan berat pada instalasi militer penting, krisis ekonomi ekstrem, atau kekacauan politik mendalam.
Pada 2002, Presiden Pervez Musharraf menyatakan bahwa “senjata nuklir Pakistan hanya ditujukan untuk India” dan hanya akan digunakan bila “keberadaan Pakistan sebagai sebuah negara” benar-benar terancam.
Dalam memoarnya, mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengaku pernah terbangun tengah malam untuk menghubungi pejabat India yang khawatir Pakistan tengah bersiap meluncurkan serangan nuklir pada tahun 2019.
Secara hampir bersamaan, media Pakistan mengutip peringatan dari pejabat tinggi: “Saya harap Anda mengerti apa arti [Otoritas Komando Nasional] dan apa saja wewenangnya. Saya katakan bahwa kami akan memberikan kejutan kepada Anda. Tunggu kejutan itu… Anda telah memilih jalan perang tanpa menyadari konsekuensinya bagi perdamaian dan keamanan kawasan.”
Pernyataan keras serupa juga terdengar selama Perang Kargil tahun 1999, ketika Menteri Luar Negeri Pakistan, Shamshad Ahmed, menyatakan negaranya “tidak akan ragu menggunakan senjata apa pun” demi mempertahankan wilayah.
Seorang pejabat AS, Bruce Riedel, mengungkap bahwa saat itu intelijen menunjukkan adanya pergerakan senjata nuklir Pakistan sebagai antisipasi.
Meskipun demikian, ada juga keraguan terhadap berbagai klaim tersebut. Ajay Bisaria, mantan Komisaris Tinggi India untuk Pakistan, menilai Pompeo terlalu membesar-besarkan ancaman nuklir maupun peran AS dalam meredakan krisis 2019. Seorang pengamat Pakistan juga menyebut bahwa selama Perang Kargil, Angkatan Udara India tidak memasuki wilayah Pakistan, sehingga tidak ada alasan nyata untuk memicu respons nuklir.
Menurut Ejaz Haider, analis pertahanan yang berbasis di Lahore, “Sinyal strategis mengingatkan dunia bahwa setiap konflik berpotensi meningkat—dan dalam kasus India dan Pakistan, risikonya lebih besar karena adanya ancaman nuklir.”
“Namun, ini bukan berarti bahwa kedua negara secara aktif mengancam menggunakan senjata nuklir.”
Namun, dalam dinamika konflik bersenjata, kadang kehancuran bisa datang bukan karena niat, tapi karena kelalaian. Profesor Alan Robock dari Universitas Rutgers menjelaskan bahwa “Hal ini bisa terjadi karena kesalahan manusia, peretas, teroris, kegagalan komputer, data satelit yang keliru, dan pemimpin yang tidak stabil.”
Contohnya terjadi pada Maret 2022, ketika India secara tak sengaja menembakkan rudal yang bisa dipasangi hulu ledak nuklir ke wilayah Pakistan, menyebabkan kerusakan pada properti sipil. Pakistan menyayangkan bahwa India tidak segera menggunakan jalur komunikasi militer atau membuat pernyataan publik dalam dua hari pertama—kelambanan yang bisa berdampak fatal jika terjadi di tengah krisis panas.
Tak lama kemudian, India memecat tiga perwira AU sebagai bentuk pertanggungjawaban atas insiden tersebut.
Christopher Clary menyebut bahwa meski ketegangan tinggi, potensi pecahnya perang nuklir masih tergolong rendah. “Selama tidak ada pertempuran darat yang besar di sepanjang perbatasan, risiko penggunaan nuklir tetap relatif kecil dan dapat dikelola,” ujarnya.
“Dalam pertempuran darat, dilema ‘gunakan atau lenyapkan’ muncul karena adanya risiko posisi darat Anda direbut musuh.”
Istilah “gunakan atau lenyapkan” mencerminkan dilema eksistensial: tekanan untuk meluncurkan senjata nuklir sebelum diserang terlebih dahulu dan kehilangan kesempatan untuk bertahan.
Sumit Ganguly dari Hoover Institution di Universitas Stanford menambahkan: “baik India maupun Pakistan tidak ingin dicap sebagai pelanggar pertama tabu nuklir pasca-Hiroshima.”
“Lebih jauh lagi, pihak mana pun yang menggunakan senjata nuklir akan menghadapi pembalasan besar-besaran dan menderita kerugian,” kata Ganguly kepada BBC.
Namun, kedua negara terus memperkuat armada senjata pemusnah massalnya. Menurut laporan The Nuclear Notebook dari Federasi Ilmuwan Amerika, Pakistan bisa memiliki hingga 200 hulu ledak pada akhir dekade ini, seiring pembangunan reaktor plutonium dan peningkatan pengayaan uranium.
Sementara itu, data dari International Panel on Fissile Materials pada awal 2023 menyebut bahwa India memiliki sekitar 680 kg plutonium tingkat senjata—cukup untuk membuat antara 130 hingga 210 hulu ledak nuklir.
Meski sejarah mencatat berbagai ketegangan yang nyaris berujung petaka, hingga kini kedua negara berhasil menghindari kehancuran nuklir.
Umer Farooq, analis dari Islamabad, mencatat bahwa “Faktor pencegahan masih berlaku. Apa yang dilakukan Pakistan hanyalah merespons serangan konvensional dengan serangan balasan konvensional mereka sendiri.”
Namun, selama bom-bom nuklir masih berada dalam jangkauan, ancaman yang terselip tidak bisa diabaikan sepenuhnya.
“Ketika senjata nuklir berpotensi terlibat, selalu ada tingkat bahaya yang tidak dapat ditoleris,” kata John Erath dari Center for Arms Control and Non-Proliferation kepada BBC.
“Pemerintah India dan Pakistan telah berhasil melewati situasi-situasi seperti ini pada masa lalu, jadi risikonya kecil. Namun, dengan senjata nuklir, bahkan risiko kecil pun terlalu besar.”