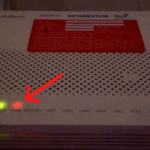Langkah kaki Presiden Suriah, Ahmed Al Sharaa, akhirnya menapaki ruang diplomasi yang dulu terasa sejauh langit dan bumi. Pada Rabu (14/5/2025), ia melakukan pertemuan langsung dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Riyadh, Arab Saudi. Keduanya bahkan terlibat dalam jabat tangan yang sarat makna, mengisyaratkan kemungkinan perubahan arah hubungan antara dua negara yang selama ini saling menuding.
Pertemuan ini difokuskan pada tawaran Trump yang ingin mengurangi tekanan ekonomi terhadap Damaskus, dengan kemungkinan pelonggaran sanksi dari Washington. Sanksi-sanksi tersebut telah membelenggu ekonomi Suriah sejak lama, dan kini muncul harapan untuk pelonggaran setelah tumbangnya rezim Bashar Al Assad oleh gerakan yang dipimpin Sharaa.
Momen ini terasa mengejutkan banyak kalangan, mengingat satu dekade sebelumnya, membayangkan tokoh seperti Sharaa berdiri sejajar dengan pemimpin Gedung Putih adalah hal yang nyaris tak masuk akal. Kala itu, Sharaa lebih dikenal sebagai musuh nomor satu negara-negara Barat, ketimbang tokoh yang layak diajak berdiplomasi.
Namun roda sejarah terus berputar. Pria yang sempat mendekam di penjara Amerika kini justru menjadi salah satu aktor utama di panggung geopolitik Timur Tengah.
Jejak Perjalanan Sharaa: Dari Lorong Gelap ke Ruang Kekuasaan
Perjalanan Sharaa bukanlah kisah yang lahir dalam semalam. Pada 2003, di tengah invasi besar-besaran Amerika Serikat ke Irak, ia bergabung dengan Al Qaeda di negara tersebut. Langkah ini menempatkannya dalam daftar buronan prioritas tinggi.
Tiga tahun kemudian, pada 2006, ia berhasil ditangkap oleh pasukan Amerika dan dibawa ke tahanan di wilayah AS, tempat ia menghabiskan beberapa tahun hidupnya di balik jeruji.
Pasca pembebasan di 2011, Sharaa kembali ke tanah kelahirannya dan ikut bergabung dalam pergolakan untuk menumbangkan Assad. Kala itu, ia beroperasi dengan nama samaran Abu Mohammad Al Golani dan memimpin Front Nusra—sebuah kelompok pemberontak bersenjata yang menjadi oposisi keras terhadap pemerintahan Assad.
Pada 2013, Washington secara resmi mencapnya sebagai teroris. Pemerintah AS menyebut bahwa Al Qaeda di Irak telah mengutus Sharaa untuk merobohkan kekuasaan Assad.
Ia kemudian membangun basis kekuatan di Idlib, provinsi di bagian barat laut Suriah, yang menjadi semacam “benteng perjuangan” bagi kelompoknya. Front Nusra pun selama bertahun-tahun beroperasi sebagai perpanjangan tangan Al Qaeda dalam perang sipil yang mengoyak Suriah.
Namun, situasi berubah ketika organisasi ekstremis ISIS mulai muncul dan menyatakan diri sebagai negara Islam. Alih-alih bergabung, Sharaa justru mengangkat senjata melawan kelompok tersebut.
Pada 2016, ia mengambil langkah drastis: memutus seluruh ikatan dengan Al Qaeda dan perlahan mulai mengarahkan kelompoknya menjadi gerakan yang lebih nasionalis, menjauh dari semangat jihad global.
Setahun berselang, pada 2017, ia menggabungkan Front Nusra dengan berbagai faksi lain dan membentuk Hay’at Tahrir Al Sham (HTS), di mana dirinya memegang tampuk pimpinan.
Menggulingkan Rezim Lama dan Membangun Babak Baru
Perjuangan untuk menjatuhkan rezim Assad terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada November 2024. Dalam serangan militer selama 11 hari, pasukan pemberontak yang dipimpin Sharaa berhasil merebut Aleppo, Homs, Hama, hingga akhirnya menembus Damaskus.
Setelah ibu kota jatuh, Assad melarikan diri ke Rusia dan meninggalkan kekuasaan yang telah ia genggam selama lebih dari dua dekade. Sharaa pun naik menjadi pemimpin sementara Suriah, sebagaimana diumumkan dalam deklarasi pada 29 Januari 2025.
Ia menyampaikan komitmennya untuk membentuk tatanan politik baru yang lebih terbuka dan merangkul semua elemen masyarakat. Dalam pidatonya, ia menyatakan tekad untuk memulihkan keutuhan wilayah Suriah, membangkitkan ekonomi yang lumpuh akibat sanksi, serta mengendalikan senjata agar kembali berada di bawah struktur resmi negara.
Pemerintah interim yang ia pimpin tidak berdiri sendiri. Dukungan dari negara-negara kawasan seperti Turkiye, Arab Saudi, dan Qatar memperkuat legitimasinya di tengah transisi pasca-Assad.