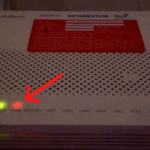Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung sukses mengadakan Seminar Internasional bertajuk “Social Media and Politics in Southeast Asia”. Acara ini berlangsung di Aula FISIP UIN SGD lantai 1 pada Kamis (13/2/2025) mulai pukul 08.30 hingga 12.00 WIB.
Seminar ini diselenggarakan oleh Centre for Asian Social Science Research (CASR) dengan menghadirkan dua akademisi ternama. Mereka adalah Ahmad Ali Nurdin, Dekan FISIP UIN SGD sekaligus pakar politik Islam, serta Merlyna Lim, seorang ahli media dan politik Asia Tenggara yang juga penulis buku Social Media and Politics in Southeast Asia (Cambridge University Press, 2024). Acara ini dimoderatori oleh Asep Iqbal, akademisi sosiologi dengan spesialisasi kajian media dan politik yang juga menjabat sebagai Direktur CASR.
Dalam paparannya, Ahmad Ali Nurdin memberikan ulasan kritis terhadap buku karya Merlyna Lim. Ia menyoroti bagaimana media sosial telah berkembang menjadi faktor utama dalam dinamika politik di kawasan Asia Tenggara. Nurdin menegaskan bahwa karya tersebut memberikan analisis mendalam tentang bagaimana platform digital mampu membentuk opini publik, menggerakkan aktivisme politik, serta memiliki peran ganda dalam mendukung atau bahkan menantang otoritarianisme. Ia menambahkan bahwa, “pengaruh media sosial bersifat paradoksal—di satu sisi, teknologi digital telah memberdayakan masyarakat sipil dalam melawan rezim otoriter, tetapi di sisi lain juga menjadi alat efektif bagi elit politik untuk mengontrol wacana publik dan mengkonsolidasikan kekuasaan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nurdin menggarisbawahi peran kapitalisme platform dalam menggeser komunikasi politik menjadi lebih berorientasi pada ekonomi perhatian. Ia menekankan bahwa algoritma media sosial cenderung lebih mendukung konten provokatif dan emosional, sehingga lebih mencerminkan budaya pemasaran algoritmik dibandingkan dengan wadah diskusi demokratis yang sehat.
Ia juga membahas bagaimana propaganda digital dan penyebaran informasi yang menyesatkan semakin terorganisir, baik oleh pihak berwenang maupun kelompok non-pemerintah. Hal ini memperkuat polarisasi politik dan mempersempit ruang kebebasan berekspresi. “Oleh karena itu, saya mengajak akademisi dan pembuat kebijakan untuk melihat media sosial bukan hanya sebagai alat komunikasi politik, tetapi juga sebagai medan pertempuran ideologi dan kepentingan ekonomi yang harus dikritisi lebih mendalam,” pesannya.
Sementara itu, Merlyna Lim menyoroti peran media sosial sebagai arena utama dalam lanskap politik Asia Tenggara. Seiring dengan meningkatnya penetrasi internet, platform digital telah menjadi sarana krusial dalam membentuk opini masyarakat, kampanye politik, hingga pergerakan sosial. Namun, ia juga mengingatkan bahwa dampaknya tidak selalu positif karena media sosial juga dapat memperparah polarisasi serta menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak akurat. “Konsep disinformation order dan post-truth politics menjadi tantangan besar dalam menjaga demokrasi di kawasan ini. Algoritma media sosial sering kali memperkuat informasi yang mendukung bias pengguna, menciptakan ‘filter bubbles’ dan ‘echo chambers’ yang mengisolasi pengguna dalam perspektif mereka sendiri,” jelasnya.
Lim menguraikan bagaimana algoritma memiliki peranan besar dalam menentukan jangkauan serta visibilitas suatu informasi politik. Ia memperkenalkan konsep algorithmic enclaves yang menggambarkan bagaimana individu cenderung terjebak dalam komunitas digital yang memperkuat keyakinan mereka sendiri. “Fenomena ini sering dimanfaatkan oleh aktor politik untuk mendominasi ruang publik dan memanipulasi opini. Saya menggarisbawahi bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi politik tetapi juga bagian dari kapitalisme platform, di mana ekonomi perhatian (attention economy) lebih diutamakan dibandingkan diskusi demokratis yang substansial,” bebernya.
Lim juga mengangkat bagaimana media sosial menjadi alat bagi aktivis dalam memperjuangkan hak-hak sipil, meskipun di saat yang sama, platform ini juga digunakan oleh rezim otoriter untuk menekan kebebasan berekspresi. Ia menyoroti gerakan seperti #MilkTeaAlliance dan #Bersih sebagai contoh bagaimana aktivisme digital dapat menantang kekuasaan yang represif. Namun, ia juga menekankan bahwa teknologi digital bisa digunakan untuk membangun citra positif tokoh politik dengan rekam jejak kontroversial melalui konsep algorithmic white branding. “Studi kasus seperti Bongbong Marcos di Filipina dan Prabowo Subianto di Indonesia menunjukkan bagaimana teknologi digunakan untuk ‘membersihkan’ sejarah politik kandidat dan menarik pemilih muda,” tuturnya.
Selain dari aspek politik, media sosial juga memiliki dimensi emosional yang kuat. Lim memperkenalkan affective binary framework, yang menggambarkan bagaimana narasi politik sering kali disajikan dalam bentuk dikotomis—”kita vs mereka”—untuk membangkitkan emosi tertentu seperti kemarahan atau solidaritas dalam suatu kelompok. Fenomena ini kerap dimanfaatkan dalam strategi kampanye populis dan politik berbasis identitas. “Oleh karena itu, pengguna media sosial harus memainkan peran sebagai agen intelektual digital yang mampu menavigasi informasi dengan sikap kritis. Hal ini menuntut posisi yang seimbang—tidak terjebak dalam bias algoritmik, tetapi juga tidak sepenuhnya menolak teknologi,” paparnya.
Baik Lim maupun Nurdin sepakat bahwa peran media sosial dalam politik di Asia Tenggara tidak dapat dilepaskan dari tantangan akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah dan masyarakat harus memahami bagaimana algoritma bekerja serta dampaknya terhadap opini publik.
Sementara itu, Asep Iqbal menegaskan pentingnya membangun kesadaran kolektif (communal consciousness) guna melawan dominasi kapitalisme pemasaran digital. Dengan demikian, masyarakat tidak sepenuhnya dikendalikan oleh algoritma yang lebih mengutamakan keuntungan platform dibandingkan dengan nilai-nilai demokrasi. “Peningkatan literasi politik dan teknologi menjadi prioritas agar masyarakat dapat lebih cerdas dalam menyaring informasi dan memahami bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan sebagai ruang demokratis yang lebih sehat,” ujarnya.
Seminar ini memberikan wawasan mendalam mengenai interaksi antara media sosial dan politik di Asia Tenggara serta tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga kebebasan berekspresi dan demokrasi di era digital. “Dengan kesadaran kritis terhadap algoritma dan strategi politik digital, masyarakat dapat menciptakan lingkungan media sosial yang lebih inklusif, tidak mudah dimanipulasi, serta tetap menjadi ruang yang mendukung demokrasi dan kebebasan berpendapat,” pungkasnya.